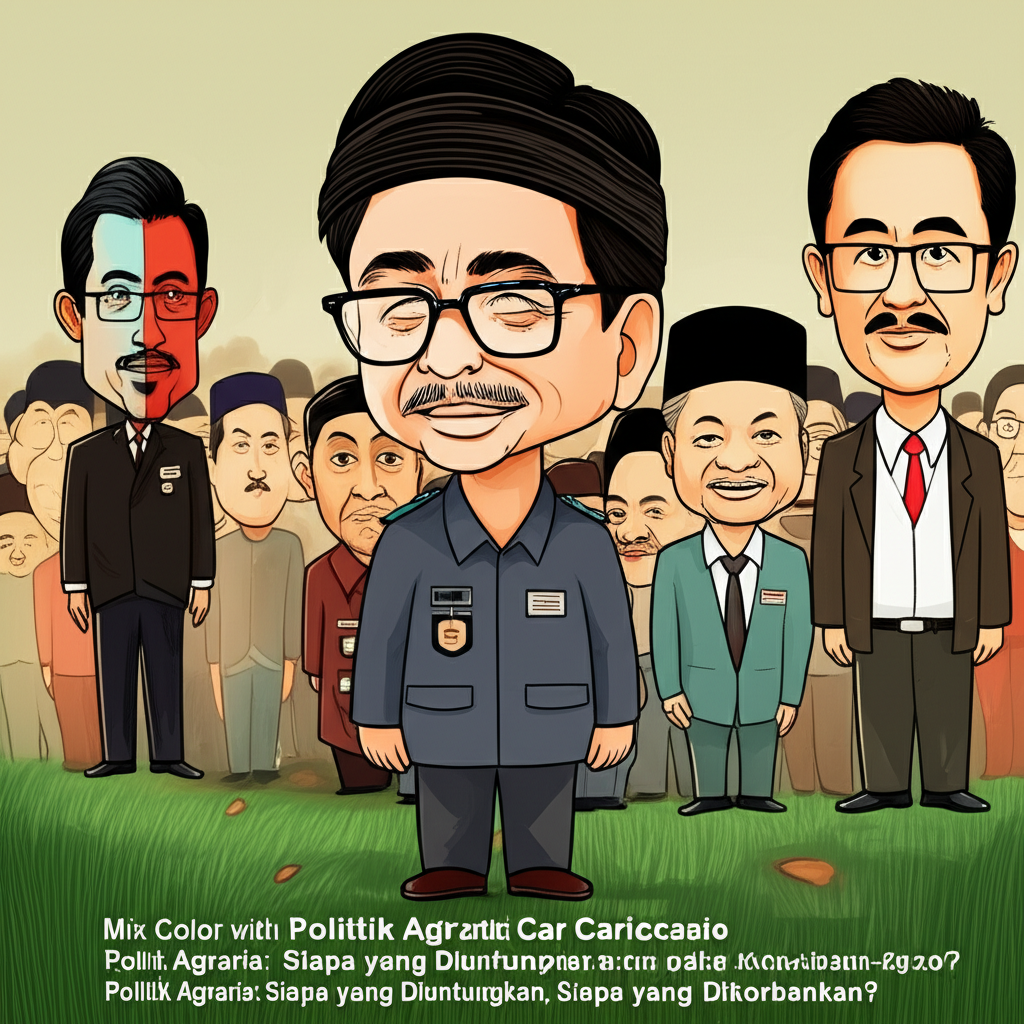Politik Agraria: Pertarungan Abadi di Atas Tanah – Siapa Meraup Untung, Siapa Tergusur dari Akar Kehidupan?
Di jantung setiap peradaban, tanah adalah lebih dari sekadar hamparan geologis; ia adalah sumber kehidupan, identitas, dan kekuasaan. Politik agraria, karenanya, bukanlah sekadar diskursus teknis tentang tata guna lahan, melainkan arena pertarungan sengit yang mencerminkan siapa yang memegang kendali atas sumber daya paling fundamental ini. Di Indonesia, sebuah negara agraris dengan sejarah panjang ketergantungan pada tanah, politik agraria adalah cermin yang jujur tentang ketimpangan, keadilan, dan masa depan bangsa. Pertanyaan krusialnya selalu sama: siapa yang diuntungkan dari kebijakan dan praktik agraria yang ada, dan siapa yang harus dikorbankan?
Pengantar: Tanah sebagai Arena Kekuasaan
Politik agraria adalah rangkaian kebijakan, regulasi, dan praktik yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah, termasuk kepemilikan, penggunaan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya agraria lainnya seperti air, hutan, dan kekayaan di bawahnya. Ini bukan isu statis, melainkan dinamis, yang terus-menerus dibentuk oleh kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Di balik setiap izin konsesi, setiap sertifikat tanah, atau setiap konflik agraria, terdapat narasi kompleks tentang kepentingan yang saling berhadapan.
Sejarah politik agraria Indonesia kaya akan dinamika tersebut. Dari warisan kolonial yang menempatkan tanah sebagai komoditas bagi kepentingan kapitalis, hingga era Orde Baru yang sentralistik dengan pembangunan berorientasi industri dan eksploitasi sumber daya alam skala besar, serta periode Reformasi yang menjanjikan pembaruan namun masih bergulat dengan implementasi. Dalam setiap fase ini, pola siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan selalu terlihat jelas.
Siapa yang Meraup Keuntungan? Hegemoni Modal dan Kekuasaan
Pihak-pihak yang paling diuntungkan dari politik agraria yang dominan saat ini adalah mereka yang memiliki akses ke modal, kekuasaan politik, dan koneksi birokrasi.
-
Korporasi Besar (Agribisnis, Pertambangan, Properti, Infrastruktur):
- Konsesi Lahan Skala Luas: Melalui izin HGU (Hak Guna Usaha) untuk perkebunan sawit, karet, atau HTI (Hutan Tanaman Industri), serta IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk batu bara, nikel, emas, dan lainnya, korporasi ini menguasai jutaan hektar lahan. Tanah yang sebelumnya dikelola secara tradisional oleh masyarakat atau merupakan hutan lindung, kini menjadi aset produktif bagi keuntungan korporasi.
- Regulasi yang Mendukung: Kebijakan pemerintah seringkali memfasilitasi investasi skala besar, dengan alasan "pembangunan nasional" atau "peningkatan devisa." Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, telah dikritik karena mempermudah perizinan bagi investasi skala besar dan melemahkan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal.
- Ekspansi Properti dan Infrastruktur: Pembangunan kota-kota baru, kawasan industri, jalan tol, dan proyek infrastruktur masif lainnya membutuhkan akuisisi lahan yang besar. Investor properti dan kontraktor infrastruktur meraup keuntungan signifikan dari kenaikan nilai tanah dan proyek-proyek ini.
-
Oligarki dan Elit Politik:
- Kepemilikan Tidak Langsung: Banyak elit politik dan birokrat memiliki saham atau koneksi dengan korporasi-korporasi besar yang bergerak di sektor agraria. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kekuasaan politik digunakan untuk mengamankan konsesi lahan, sementara keuntungan dari lahan tersebut memperkuat posisi politik mereka.
- Renumerasi dan Gratifikasi: Proses perizinan lahan yang kompleks seringkali membuka celah untuk praktik korupsi, di mana "pelicin" atau "uang komisi" menjadi bagian tak terpisahkan dari pengamanan izin.
-
Negara (melalui Pajak dan Devisa):
- Secara formal, negara mendapatkan pemasukan dari pajak dan royalti dari kegiatan agraria skala besar. Argumen pembangunan seringkali digunakan untuk membenarkan pengorbanan sosial dan lingkungan, dengan janji peningkatan PDB dan devisa. Namun, distribusi manfaat ini seringkali tidak merata dan tidak sampai ke tingkat lokal.
Siapa yang Dikorbankan? Jutaan Jiwa di Akar Kehidupan
Di sisi lain, daftar pihak yang dikorbankan jauh lebih panjang dan pilu, mencerminkan ketidakadilan struktural yang mendalam.
-
Petani Kecil dan Buruh Tani:
- Kehilangan Tanah (Land Grabbing): Ini adalah korban paling langsung. Tanah-tanah garapan turun-temurun, baik yang bersertifikat atau berdasarkan hak adat, seringkali digusur demi proyek perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur. Mereka kehilangan sumber penghidupan utama, yang seringkali berarti jatuh ke jurang kemiskinan dan menjadi buruh di tanah mereka sendiri yang kini dikuasai korporasi.
- Kriminalisasi: Ketika petani mempertahankan tanahnya dari penggusuran, mereka seringkali menghadapi tuduhan kriminalisasi seperti "perusakan" atau "penyerobotan lahan," yang berujung pada penangkapan dan penahanan.
- Ketergantungan dan Marginalisasi: Bagi mereka yang tersisa, kebijakan pertanian yang berpihak pada agribisnis besar seringkali membuat petani kecil kesulitan bersaing, terjerat utang, dan bergantung pada pasar yang dikendalikan korporasi.
-
Masyarakat Adat:
- Kehilangan Wilayah Adat dan Identitas: Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga identitas, sejarah, budaya, dan spiritualitas. Penggusuran wilayah adat berarti penghancuran seluruh tatanan sosial dan budaya mereka, mengikis pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya.
- Pencemaran Lingkungan: Operasi pertambangan atau perkebunan skala besar seringkali mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah, merusak ekosistem yang menjadi sandaran hidup masyarakat adat dan menghilangkan akses mereka terhadap sumber daya alam yang bersih.
- Minimnya Pengakuan Hukum: Meskipun ada amanat konstitusi dan putusan MK tentang pengakuan masyarakat adat, implementasi di lapangan masih sangat lambat dan diskriminatif.
-
Lingkungan Hidup:
- Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan adalah pendorong utama deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Ini berdampak pada perubahan iklim global.
- Bencana Ekologis: Banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan seringkali merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi agraria yang tidak berkelanjutan. Masyarakat lokal adalah yang pertama dan paling parah merasakan dampaknya.
-
Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya:
- Perempuan di pedesaan seringkali menjadi pihak yang paling terdampak ketika tanah hilang, karena mereka adalah pilar ketahanan pangan keluarga dan pengelola sumber daya sehari-hari. Ketika akses ke tanah dan sumber daya alam hilang, beban kerja mereka meningkat, dan kerentanan ekonomi mereka memburuk.
Dinamika Konflik dan Jalan Menuju Keadilan Agraria
Konflik agraria di Indonesia adalah realitas sehari-hari. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan ribuan kasus konflik yang melibatkan jutaan hektar lahan dan jutaan jiwa, dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Konflik ini adalah manifestasi dari:
- Ketidakjelasan Hukum dan Tumpang Tindih Aturan: Banyak wilayah yang diklaim oleh masyarakat lokal atau adat tidak memiliki legalitas formal di mata negara, sehingga mudah diklaim oleh korporasi.
- Lemahnya Penegakan Hukum: Bahkan ketika ada aturan yang berpihak pada rakyat, penegakannya seringkali lemah, bahkan cenderung berpihak pada pemodal.
- Ketiadaan Political Will: Komitmen untuk menjalankan Pembaruan Agraria Sejati (PAS) yang diamanatkan UUPA 1960 masih sering terbentur kepentingan politik dan ekonomi.
Mewujudkan keadilan agraria membutuhkan lebih dari sekadar retorika. Ini menuntut:
- Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Petani dan Masyarakat Adat: Percepatan reforma agraria sejati, redistribusi tanah yang adil, dan pengakuan serta perlindungan hukum atas wilayah adat adalah kunci.
- Penegakan Hukum yang Adil: Pemerintah harus berdiri di atas semua kepentingan, menghentikan kriminalisasi petani, dan menindak tegas korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Prioritas harus diberikan pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
- Transparansi dan Partisipasi Publik: Proses perizinan dan tata kelola lahan harus transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal yang terdampak.
Kesimpulan: Membangun Masa Depan di Atas Keadilan Tanah
Politik agraria adalah pertarungan abadi di atas tanah, antara kepentingan modal dan hak-hak rakyat, antara pembangunan yang eksploitatif dan keberlanjutan yang inklusif. Saat ini, keuntungan masih terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara jutaan jiwa harus menanggung beban pengorbanan yang berat, terenggut dari akar kehidupannya.
Masa depan Indonesia, dan ketahanan bangsanya, sangat bergantung pada bagaimana kita menyelesaikan pertarungan ini. Memilih untuk terus mengorbankan rakyat dan lingkungan demi keuntungan sesaat adalah jalan menuju kehancuran sosial dan ekologis. Namun, jika kita berani memilih keadilan, dengan mengembalikan kedaulatan atas tanah kepada mereka yang berhak dan mengelola sumber daya secara bijaksana, barulah kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa. Tanah ini, sejengkal demi sejengkal, menanti keputusan kita.