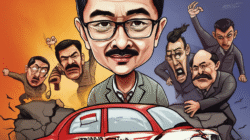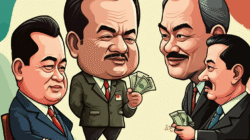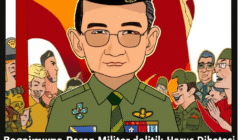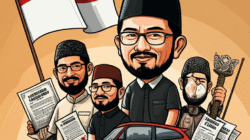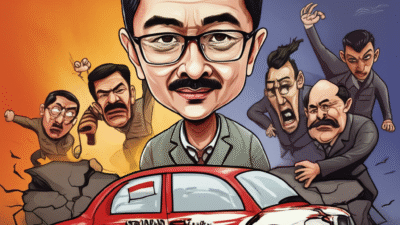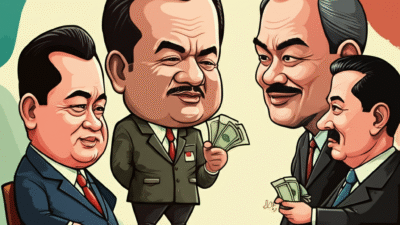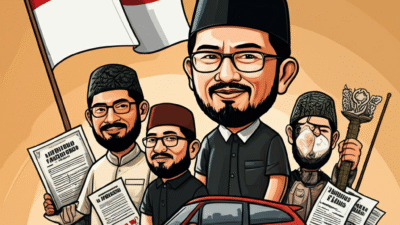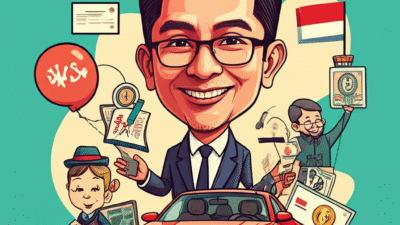Identitas sebagai Pedang Bermata Dua: Mengapa Politik Primordialisme Tak Pernah Tumpul dalam Kontestasi Elektoral?
Dalam setiap siklus pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, satu fenomena yang tak pernah absen dari panggung politik adalah bangkitnya politik identitas. Meskipun retorika kampanye seringkali menyerukan pentingnya program, visi, dan misi, pada kenyataannya, politik identitas — yang bermain di ranah sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) — acapkali menjadi senjata paling ampuh untuk menggaet suara pemilih. Pertanyaan krusialnya adalah, mengapa strategi yang seringkali memecah belah ini masih menjadi "raja" dalam kontestasi elektoral?
Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara psikologi massa, struktur sosial, dan strategi politik yang pragmatis. Mari kita bedah lebih dalam.
1. Kekuatan Emosi Mengalahkan Rasionalitas
Politik identitas bekerja dengan memanfaatkan ikatan emosional dan primordial yang sangat kuat dalam diri manusia. Rasa memiliki terhadap kelompok (agama, etnis, daerah) adalah kebutuhan dasar psikologis yang seringkali lebih dalam dan mendesak daripada pertimbangan rasional tentang program ekonomi atau kebijakan publik. Ketika seorang kandidat atau partai mampu mengasosiasikan diri dengan identitas tertentu dan memposisikan lawan sebagai "yang lain" atau bahkan "ancaman," ia secara efektif mengaktifkan naluri solidaritas dan pertahanan kelompok.
Narasi "kami melawan mereka" ini jauh lebih mudah dicerna dan disebarkan dibandingkan penjelasan rumit tentang inflasi atau reformasi birokrasi. Pemilih cenderung merasa lebih aman dan terwakili ketika mereka melihat "salah satu dari kita" berkuasa, terlepas dari rekam jejak atau kapasitasnya. Loyalitas identitas seringkali bersifat mutlak, mengabaikan kekurangan dan membesarkan kelebihan dari kelompok sendiri, sekaligus menafikan kelebihan dan memperbesar kekurangan kelompok lain.
2. Retakan Sosial yang Sudah Ada
Masyarakat Indonesia, seperti banyak masyarakat multikultural lainnya, memiliki retakan sosial (cleavages) yang sudah terbentuk sejak lama berdasarkan perbedaan etnis, agama, geografis, hingga kelas sosial. Para politisi yang cerdik tidak menciptakan perpecahan ini, melainkan mengeksploitasinya. Mereka hanya perlu menyiramkan bensin ke bara api yang sudah ada, mengubah perbedaan menjadi polarisasi, dan polarisasi menjadi alat mobilisasi suara.
Misalnya, isu agama dapat dengan mudah digoreng untuk memecah belah pemilih di wilayah yang memiliki komposisi demografi religius yang heterogen. Demikian pula dengan isu etnis di daerah-daerah yang kaya akan keragaman suku. Isu-isu ini tidak perlu diciptakan dari nol; mereka sudah menjadi bagian dari struktur sosial dan sejarah yang bisa diungkit kapan saja untuk kepentingan politik jangka pendek.
3. Peran Media Sosial dan Ruang Gema (Echo Chamber)
Di era digital, media sosial telah menjadi medan pertempuran utama bagi politik identitas. Algoritma platform media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan pengguna, menciptakan "ruang gema" atau echo chamber. Dalam ruang ini, informasi yang memperkuat bias identitas seseorang akan terus-menerus disajikan, sementara pandangan yang berbeda akan disaring.
Hal ini memperparah polarisasi. Hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang berbasis identitas dapat menyebar dengan kecepatan kilat, membentuk narasi yang kuat dan sulit dibantah oleh fakta. Para pemilih menjadi semakin terisolasi dalam gelembung informasi mereka sendiri, memperkuat keyakinan bahwa kelompok mereka adalah yang paling benar dan kelompok lawan adalah ancaman. Kampanye politik identitas pun semakin efektif karena mampu menargetkan audiens spesifik dengan pesan yang sangat personal dan memicu emosi.
4. Lemahnya Politik Programatik dan Minimnya Literasi Politik
Salah satu alasan mengapa politik identitas tetap dominan adalah karena seringkali tidak ada alternatif yang kuat berupa politik programatik yang berbasis data dan solusi. Menjelaskan kebijakan ekonomi yang kompleks atau reformasi sistematis membutuhkan waktu, usaha, dan tingkat literasi politik yang tinggi dari pemilih. Banyak pemilih, yang disibukkan dengan urusan sehari-hari, cenderung lebih mudah tertarik pada narasi yang sederhana, personal, dan emosional.
Para kandidat pun terkadang enggan atau tidak mampu menyusun program yang konkret dan menarik. Lebih mudah bagi mereka untuk mengandalkan sentimen identitas yang sudah ada, karena itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan dukungan massa tanpa harus bersusah payah merumuskan solusi atas masalah riil. Akibatnya, diskursus publik dalam pemilu menjadi dangkal, minim debat substantif, dan lebih banyak berkutat pada isu-isu personal atau identitas kandidat.
5. Efektivitas Mobilisasi Massa
Secara pragmatis, politik identitas adalah alat mobilisasi massa yang sangat efektif. Ketika sebuah kelompok merasa identitasnya terancam atau terwakili, tingkat partisipasi politik mereka bisa melonjak tajam. Rasa solidaritas dan "perjuangan" untuk kelompok sendiri dapat mendorong pemilih untuk datang ke TPS, bahkan jika mereka sebelumnya apatis terhadap politik. Ini menjadi daya tarik bagi politisi yang membutuhkan angka partisipasi tinggi dari basis suara mereka.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Dominasi politik identitas dalam pemilu memang efektif untuk meraih kekuasaan, namun dampaknya bagi persatuan dan kemajuan bangsa sangat merugikan. Ia dapat mengikis semangat kebangsaan, memicu konflik sosial, dan menghambat dialog konstruktif tentang masalah-masalah substantif yang dihadapi masyarakat. Proses demokrasi menjadi arena pertarungan identitas, bukan ajang adu gagasan dan solusi.
Untuk keluar dari jebakan ini, diperlukan upaya kolektif:
- Peningkatan Literasi Politik: Edukasi masyarakat agar mampu berpikir kritis, membedakan fakta dari hoaks, dan menilai kandidat berdasarkan visi-misi dan rekam jejaknya, bukan hanya identitas.
- Tanggung Jawab Elit Politik: Para politisi harus berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi isu SARA dan fokus pada politik programatik yang membangun.
- Peran Media dan Sipil: Media harus menyajikan informasi yang berimbang dan mendidik, sementara masyarakat sipil harus aktif mengkampanyekan persatuan dan toleransi.
Selama politik identitas masih menjadi jalan pintas paling efektif menuju kekuasaan, ia akan terus menjadi senjata utama dalam pemilu. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengubah arah kompas politik agar lebih berorientasi pada masa depan, bukan sekadar terjebak dalam primordialisme masa lalu.